Tarian Sepenuh Jiwa
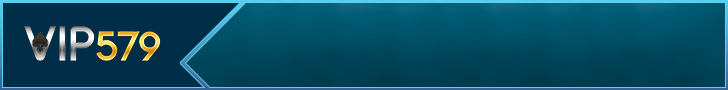
.gif)





Dengan rambut yang kini meriap menyentuh bahu, hidung bangir yang tegak di antar dua mata bak telaga bening, dan bibir basah yang selalu siap menyungging senyum, Rien adalah Dang Hyang Tari: seorang queen of the dance terkenal di ibukota. Apalagi ia adalah juga pencipta, seorang koreografer ulung yang mencampurkan tradisi dan modernisasi. Satu tariannya, The Cocoon mengundang pujian setinggi langit dari para kritikus dalam dan luarnegeri. Itulah tarian sepenuh jiwa tentang kempompong yang berubah menjadi kupu-kupu.
Di bawah sorot tunggal lampu panggung yang kosong (kecuali oleh sebuah pohon hidup setinggi satu setengah meter di tengahnya), Rien meliukkan tubuhnya yang terbungkus kain putih sekujur badan, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gerakannya aneh, sekaligus magis karena ada warna tarian wilayah Indonesia Timur, sedikit Bali, ditambah sedikit gerakan Serampang Duabelas, juga penuh lentingan-lentingan yang sulit ditiru. Seperti tari-tari balet modern. Kadang-kadang ia meliuk ke belakang sampai punggungnya hampir menyentuh lantai panggung; lalu memutar sambil menjulur ke atas dalam gerakan lembut; lalu tangannya terentang menerobos keluar dari balutan kain; lalu kelima jarinya merentang dan bergerak cepat seperti digetarkan oleh motor listrik. Satu cincin yang dipakai di jari tengahnya, berkerejap-berkilau bagai pemantik laser.
Penonton kerap bertepuk tangan. Kritikus tari duduk terpana di baris depan. Media massa segera meliput kemana pun ia pergi. Namanya pun melejit: Rienduwati, Ratu Baru Dunia Tari. Sebuah stasiun televisi mewawancarainya di belakang panggung. Wajahnya sumringah masih berpeluh. Tubuhnya yang agak kurus tetapi padat-berisi, terbungkus ketat oleh baju kaos dan celana panjang hitam. Matanya itu….. Ya, matanya terus berbinar sepanjang wawancara. Dan ia bercerita tentang kegairahan mencipta tarian-tarian modern yang tak sepenuhnya melupakan tradisi lokal. Bercerita tentang karya monumentalnya, The Cocoon itu. Konon itulah pula ekspresi jiwanya.
“Mengapa harus kepompong, Mbak Rien?” tanya si pewawancara, seorang gadis muda yang tampak sekali mengagumi tokoh yang diwawancarainya.
“Ya, dia itu, kan, menjelma dari tidur panjang penuh penantian, ke kemerdekaan yang bisa membuatnya terbang. Aku menyimpulkan metamorfosa itu sebagai suatu yang megah, sekaligus rumit. Bayangkan saja, betapa bedanya antara ulat yang uget-uget, lalu kepompong yang patuh dan diam, lalu kupu-kupu yang indah!” kata Rien bersemangat, dalam satu tarikan nafas yang panjang.
Si pewawancara agak menganga, dan sempat dua atau tiga detik lupa mengajukan pertanyaan berikutnya. Untunglah Rien sangat santai, dan malah bercanda menepuk lengan pewawancaranya sambil berucap, “Begitulah kira-kira, jeng!”
Demikianlah nama Rien semakin mencuat. Apalagi kemudian ia sering menari di pusat-pusat kebudayaan asing di ibukota. Tak lama setelah debut-nya di Gedung Kesenian, Rien pun berkeliling Eropah selama satu bulan penuh; menari di beberapa festival di Jerman, Perancis, Inggris dan Italia. Usianya masih sangat muda untuk ukuran koreografer sekaliber itu. Ia sedang menapak angka 30. Tetapi kalau melihat penampilannya yang ceria, segar, dan enerjik, orang pasti menyangka ia baru berusia 20-an. Dan ia masih melajang walau sudah tinggal di apartemen mewah dan punya sebuah BMW hadiah sepasang suami-istri pengusaha Jerman yang terkagum kepadanya.
Beberapa kali pria mencoba mendekatinya, tetapi ditampik dengan halus. Alasan terkuat yang diajukan Rien adalah: ia terlalu sibuk dengan sanggar dan tariannya. Dan memang ia sangat sibuk di tahun-tahun pertama karirnya. Setelah The Cocoon, ia menciptakan dua karya cemerlang lagi. Satu diberi judul Padi – Kapas, ditarikan berpasangan dengan seorang penari pria asal Riau. Satu lagi bernama Serambi Para Gadis yang dinarikannya bersama 6 penari pengiring wanita. Kalau The Cocoon mengesankan kecanggihan Rien sebagai penari tunggal, maka dua karya lainnya ini memastikan Rien sebagai koreografer yang telah matang.
Tetapi setelah beberapa saat menjadi lajang paling populer seantero ibukota, Rien akhirnya luluh juga. Ada seorang pria yang mendekat kepadanya, dan koran atau majalah mulai bergosip tentang mereka. Namanya Tiyar, seorang gitaris kelompok jazz yang berjumpa-pandang dengan ratu tari itu pada sebuah acara kesenian yang diadakan Pusat Kebudayaan Jepang. Tiyar adalah pemuda berdarah campuran. Ibunya orang Jepang. Ayahnya seorang Indo-Belanda. Oleh sebab itu ia bertampang unik, dengan mata Eropa yang kebiruan tetapi rambut Asia yang hitam legam. Semua orang bilang ia cute. Maka ia pun punya rasa percaya-diri yang cukup melimpah. Maka ia pun dengan gagah menegur lebih dahulu sambil memandang takjum sekaligus takjim.
“Halo, tarian Anda sungguh mengagumkan…,” katanya sambil mengacungkan tangan untuk bersalaman.
Rien memandang pemuda bercelana jeans dan berkaos putih di depannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu ia tersenyum, tetapi tidak menyambut tangan yang telah tersodor.
“Saya Tiyar, gitaris yang sebentar lagi manggung..,” kata Tiyar tetap gagah berani, walau tangannya terpaksa ditarik kembali.
“Saya Rien, penari yang baru turun dari panggung,” jawab Rien ringan sambil melap lehernya dengan sapu tangan. Harum semerbak menyebar dari setangan tipis itu.
“Riendu. Saya sudah tahu nama Anda. Semua orang sudah tahu,” kata Tiyar masih dengan gaya penuh percaya diri.
“Apakah orang juga tahu nama Tiyar?” ucap Rien yang tiba-tiba ingin mencandai pemuda cakep yang … ah, kenapa ia tiba-tiba ingat seorang pemuda secakep ini di masa lampaunya, di kampung sana?
Tiyar tersipu, “Wah, pasti belum banyak yang tahu saya,” katanya sambil melangkah merendengi Rien yang menuju kamar ganti pakaian.
“Ini jalan menuju kamar ganti, lho..,” kata Rien santai, “Kalau panggung, ke arah yang berlawanan.”
Tiyar menggaruk kepalanya yang tidak gatal, “Saya mau menanyakan sesuatu kepada Anda,” katanya sambil terus merendengi Rien. Beberapa kru band melihat ke arah mereka, dan salah seorang bersuit-suit menggoda.
“Oh! .. saya kira mau minta tandatangan,” kata Rien lagi sambil tertawa kecil. Boleh, dong, sekali-kali menggoda pemain band, ucapnya dalam hati.
“Berapa nomor telepon rumah Anda?” tanya Tiyar sebelum keberaniannya hilang.
Mereka sudah sampai di depan kamar ganti khusus untuk Rien, dan wanita itu membalikkan badan menghadapi Tiyar yang kini terdiam menunggu jawaban bagai seorang terdakwa menunggu keputusan hakim.
“Mau mengajak makan malam?” tanya Rien dengan ringan, seakan-akan bertanya kepada seorang yang sudah dikenalnya lama. Tetapi justru pertanyaan seperti ini yang tidak diduga oleh Tiyar.
“Eh.. ah, bukan begitu,” ucap pemuda itu gugup, “Saya cuma ingin tahu nomor telepon…”
Rien tersenyum manis dan penuh godaan. Rasain! sergahnya dalam hati sambil berbalik dan masuk ke ruang ganti. Lalu sambil tetap tersenyum ia melirik sekali lagi ke Tiyar yang terpaku di depan pintu. Lalu ia tutup pintu kamar gantinya. Tiyar pun hilang dari pandangan mata. Kalau memang ia memerlukan nomor teleponku, pikir Rien, biarlah ia berusaha sedikit lebih keras.
*****
Dan berusahalah Tiyar lebih keras. Agak sulit mulanya, karena Rien memang tidak mengumbar nomor telepon pribadi. Dia biasa dihubungi di sanggarnya. Karena itulah Tiyar ke sana. photomemek.com Berkali-kali ke sana, hanya untuk menunggu Rien berhenti melatih atau berlatih. Sudah dua kali ia datang, tetapi Rien masih harus melatih anak buahnya. Tiyar pulang dengan tangan hampa.
Pada suatu hari ia menunggu tak kurang dari 1 jam, hanya untuk kecewa karena sebuah stasiun televisi Jerman ternyata punya janji wawancara.
“Tetapi saya sudah di sini sejak 1 jam yang lalu, Rien!” protes Tiyar ketika Rien dengan ringannya melambaikan tangan sebelum menuju kolam ikan di bawah pohon perdu, tempat ia menerima kru televisi Jerman itu.
“Aku tahu,” ujar Rien sambil menembakkan lirik matanya yang bisa menumbangkan beringin itu.
“Lalu, musti menunggu berapa lama lagi?” kejar Tiyar.
“Dua, ….. mungkin tiga, mungkin empat jam,” jawab Rien ringan. Langkahnya gemulai tetapi cukup cepat untuk membuat Tiyar tergopoh-gopoh di belakangnya.
Tiyar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sial, umpatnya dalam hati, dua jam lagi aku janji latihan band.
Kru televisi kemudian mengatur berdiri Rien, dekat sebuah patung batu di pinggir kolam. Suara gemercik air terdengar lamat-lamat. Sinar mentari tak terlalu banyak, tetapi ada beberapa lampu sorot dan reflector yang dibawa khusus untuk memberi efek cahaya sempurna. Seorang juru rias dengan sigap memupuri muka Rien yang berdiri patuh. Sementara Tiyar berdiri di kejauhan, masih bimbang apakah akan menunggu atau mengulang usahanya besok.
Rien memandang pemuda itu berdiri di bawah sebuah pohon. Ketika itulah, ketika melihat pohon itu, …. melihat seorang pemuda berdiri di bawahnya dengan wajah penuh harap…. Rien tiba-tiba teringat lagi seseorang dari masa lalunya. Suasananya mirip: latihan menari, dan seseorang yang menunggu! Ingatan itu seperti menyelinap dan muncul tiba-tiba di depan mata-hatinya. Ingatan itu juga seperti sebuah cubitan; tidak sakit, tetapi cukup menyengat. Sebuah perasaan hangat yang sulit dicerna tiba-tiba memenuhi dadanya. Di manakah dia sekarang? bisik Rien dalam hati.
Tiyar melihat Rien memandang ke arahnya. Pemuda itu menoleh ke belakang. Ia ragu-ragu, benarkah wanita mempesona itu sedang memandangnya, atau pohon di belakangnya? Ketika pasti bahwa tidak ada siapa-siapa di belakangnya, kecuali sebuah pohon yang tak begitu menarik, Tiyar menoleh kembali ke Rien. Dan Rien tersenyum. Jantung Tiyar berdegup setengah kali lebih cepat dari sebelumnya. Cepat-cepat ia membalas senyum itu. Dan Rien tersenyum lebih lebar lagi, memperlihatkan sederet giginya yang bak mutiara itu. Wahai, Tiyar seperti disiram air sejuk di tengah siang yang kerontang ini. Lalu bibir Rien bergerak, mengucapkan sesuatu tetapi tak terdengar.
“Apa?” tanya Tiyar dengan suara keras, membuat semua orang menengok ke arahnya.
“Besok!” teriak Rien membalas, dan semua orang menengok ke arah wanita itu.
“Apanya yang besok?” teriak Tiyar. Semua orang menengok ke pemuda itu lagi.
“Besok jam 4 sore. Aku tunggu di sini!” sahut Rien. Semua orang tidak menengok ke wanita itu lagi, melainkan memandang pemuda itu. Menunggu reaksinya.
Tiyar berpikir cepat. Besok ada janji dengan salah satu majalah musik. Bisa ditunda! Maka cepat-cepat ia mengepalkan tinju, lalu membuat gerakan membetot dengan tangannya sambil berteriak “Yes!”
Rien tertawa renyai melihat tingkah pemuda itu. Semua orang ikut tertawa. Pemimpin kru televisi bahkan bertepuk tangan. Juru rias sejenak menggeleng-gelengkan kepalanya. Kameraman yang bertolak-pinggang dan berwajah angker itu pun ikut tersenyum. Tiyar was terribly happy!
*****
Begitulah akhirnya Tiyar menjadi pacar Rien setelah delapan makan malam, satu kencan di disko, dan satu kali pergi bareng ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu.
Sekarang, kemana pun Rien manggung, pasti ada Tiyar. Kemana pun band Tiyar menggelar jazz-rock-nya, ke sanalah Rien pergi. Pasangan itu tampak serasi. Yang satu tampak gagah dengan tubuh selalu terbungkus t-shirt putih bersih. Yang satu tampak cantik walau juga cuma dibungkus t-shirt ungu atau hitam. Keduanya selalu memakai celana jeans. Konon, setiap membeli jeans, pasti sepasang. Media massa sibuk membuat spekulasi. Pertanyaannya satu: kapan mereka menikah?
Padahal usia mereka terpaut hampir 3 tahun. Seorang jurnalis iseng mengangkat topik ini, tetapi ia didamprat redakturnya. Kata redakturnya yang berkaca-mata tebal dan berusia hampir 60 tahun itu, jangan memancing kemarahan pembaca yang tidak peduli pada usia, dan yang ingin terus membaca kisah dewa-dewi. Maka sang jurnalis yang baru berusia 25 tahun itu dengan cemberut menghapus alinea-alinea yang menyoal usia Rien dan Tiyar.
Tetapi sesungguhnyalah soal usia ini jadi topik cukup hangat di antara mereka berdua. Misalnya, pada sebuah malam penuh bintang, ketika dengan manja Rien duduk di pangkuan Tiyar di tepi pantai, pemuda itu berbisik di telinganya, “Kapan aku bisa menyusul usia kamu?”
“Kalau kamu sudah bisa beli mesin waktu!” sergah Rien sambil mengucek-ucek rambut kekasihnya.
“Berapa harga mesin waktu?” bisik Tiyar sambil mencium leher Rien yang selalu semerbak itu.
“Tanya saja di tokonya,” kata Rien sambil mendorong tubuhnya ke belakang, menyandar sepenuhnya ke dada Tiyar yang kokoh dan bidang itu.
“Bagaimana kalau kamu saja yang mengurangi usiamu?” kata Tiyar sambil melingkarkan tangannya di pinggang Rien. Hmm.., nyaman sekali mendekap tubuh kekasih di depan debur ombak dan di bawah sejuta bintang.
“No way!” sergah Rien sambil mencubit lengan kekasihnya gemas.
“Aduh! Kenapa harus mencubit, sih?!”
“Gemes! Kamu suka tanya-tanya yang tidak bisa dijawab!” sergah Rien mencubit lagi.
Tiyar mengaduh lagi. Juga mengaduh dalam hati, karena sesungguhnya ia agak risau dengan perbedaan usia. Seorang rekan satu band pernah bertanya menyindir, apakah enak menjadi daun muda. Kalau itu bukan si Gatot yang ototnya diperlukan untuk menabuh drum, pasti Tiyar sudah meninjunya!
Rien juga tahu apa yang di-aduh-kan Tiyar. Maka ia membalikkan tubuhnya, duduk di pangkuan Tiyar sambil menghadapnya. Kedua tangannya dikaitkan ke leher pemuda itu. Pandangan mereka beradu. Rien tersenyum, lalu mengecup bibir pemuda itu sekilas.
“Kamu risau soal usia lagi, ya!?” ucap Rien setengah berbisik.
Tiyar mengangguk sambil memandang dua telaga bening di depannya. Oh, sejuk sekali telaga itu. Bisakah ia berenang di sana?
“Kenapa musti risau?” tanya Rien lagi sambil mengecup ujung hidung pemuda itu dengan lembut.
“Karena aku ingin menikahimu,” kata Tiyar tegas. Ini adalah kali ketiga ia mengatakan kalimat yang persis sama, kata demi kata.
Rien tertawa renyai. Ia sudah bisa menduga jawabnya. Dan ia juga sudah selalu menjawabnya dengan tak kalah tegas, “No way, Hosey!”.
“Apakah karena aku lebih muda?” desak Tiyar.
“Bukan-bukan-bukan,” kata Rien sambil berdendang. Ada lagu dang-dut yang berisi lirik itu. Rien suka menggoda Tiyar dengan mengatakan bahwa dang-dut lebih mudah dicerna daripada lengkingan gitar jazz.
“Ayolah kita menikah, Rien!” ujar Tiyar sambil merengkuh tubuh kekasihnya, lalu mencium bibirnya yang ranum itu. Rien sejenak gelagapan. Ia melepaskan diri dengan mendorong sekuat tenaga.
“Kamu mengajak menikah seperti mau memperkosa!” sergah Rien sambil tertawa.
“Sekarang aku yang gemes. Ayo kita kawin!” kata Tiyar mencoba mencium lagi, tetapi gagal.
“Jangan di sini,” kata Rien sambil tertawa nakal. Tiyar semakin gemas. Direngkuhnya kuat-kuat tubuh mungil yang sintal-padat itu. Diciumnya bibir merekah-basah yang menggairahkan itu. Dilumatnya sepenuh hati. Dibuatnya Rien mengerang-mendesah. Tiyar tidak peduli dan terus mencium. Panjang dan lama sekali ciuman itu. Kira-kira 12 menit 32 detik.
“Pulang, yuk?” bisik Rien dengan nafas memburu ketika ciuman mereka usai.
“Your place or mine?” bisik Tiyar juga dengan nafas memburu.
“Ke sanggar saja!” desah Rien. Itu adalah permintaan yang tak mengherankan Tiyar. Wanita pujaannya ini punya sebuah kamar yang mirip gua pertapaan di sanggarnya. Di sana cuma ada kasur berlaskan tikar rotan Kalimantan. Seluruh lantainya ditutupi tikar pandan dengan corak tradisional, berwarna hijau-kuning-merah yang agak kusam. Dindingnya dihiasi berbagai kain tenun Sumbawa. Ada pula sebuah kain tenun Sumatera Barat terselampir seenaknya. Di pojok ruangan ada dudukan lampu setinggi satu meter, terbuat dari padas. Kalau lampu dinyalakan, cahayanya hanya temaram saja, seperti lampu sentir minyak tanah di desa-desa. Di salah satu dinding ada cermin besar yang bisa memantulkan seluruh isi ruang. Di kamar itulah Rien mencipta banyak tarian, termasuk tiga masterpieces-nya.
*****
Di “gua pertapaan” Rien itulah mereka juga sering bercinta dan bercinta lagi.
Rien menumpahkan segala kegairahan badaniahnya di atas tubuh kokoh kekasihnya. Ia seperti tak letih-letihnya menggumuli tubuh yang dengan sukahati melayani segala permintaannya itu. Bagi Rien, pemuda ini adalah lover boy yang mengagumkan. Dengan pemuda inilah ia bisa mengarungi samudera sensual yang penuh dengan puncak-puncak ombak kenikmatan itu. Ia bisa leluasa duduk di pinggul pemuda itu, merasakan dirinya bagai dipancang-tegak oleh kekuatan yang nyaris tak pernah sirna. Ia bisa bebas bergerak, bahkan menarikan tarian erotik, di atas tubuh yang berpeluh itu. Lagi dan lagi ia merengut puncak demi puncak kenikmatan, yang makin lama makin tinggi menggapai langit birahi.
Sejak berpacaran dengan Tiyar, ada sesuatu yang terbangkit di diri Rien. Entah betul, entah tidak. Gairah sensual Rien selalu menggebu pada percumbuan mereka. Anehnya, setiap kali sehabis bercinta dengan pemuda itu, selalu datang inspirasi indah untuk sebuah tari. Seringkali setelah pemuda itu pulang, setelah Rien puas tergeletak di kasur percintaan mereka, datang ide untuk gerakan-gerakan tari. Lalu, malam-malam, atau pagi-pagi sekali, Rien bangun untuk mematangkan ide itu. Bertelanjang dada ia menari sendirian di depan cermin, mencoba gerakan-gerakan baru dan mencatat setiap gerak yang telah ia rasakan sempurna.
Apakah semua seniman begitu? Apakah semua seniman memakai sumberdaya seksual untuk pemicu daya cipta? Mungkinkah ada hubungan antara orgasme dan ide yang cemerlang? Ah, pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah terjawab oleh Rien. Ia juga akhirnya tak peduli, dan tak pernah mau mencoba membuktikan benar-tidaknya. Ia terus saja berkarya, dan terus pula bercinta.
Tiyar pada mulanya terkejut ketika mereka pertama-kali bercinta, kira-kira empat bulan yang silam, atau tiga bulan setelah perkenalan mereka. Tidaklah ia menyangka bahwa wanita cantik yang cerdas dan kreatif itu ternyata adalah seorang petualang sensual di atas ranjang. Tiyar pada awalnya berlaku sopan dalam bercinta, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak mengejar badan melainkan hati wanita itu. Tetapi setelah dua kali bercinta, Tiyar tak peduli lagi. Ia pun melayani saja segala permintaan Rien, betapa pun liar dan sensualnya permintaan itu.
Seperti malam ini, di awal percumbuan, Rien berbisik serak, “Eat me, please…”. Dan Tiyar pun dengan senang hati memenuhi permintaan itu. Dan wanita itu mengerang-erang menikmati tiga kali puncak kenikmatan. Tubuh bagian atasnya masih terbungkus lengkap. Hanya dari pinggang ke bawah yang terbuka-bebas. Sebuah kursi rotan dibawa masuk kamar, khusus untuk itu. Dan di atas kursi itu Rien menggelepar-geleparkan orgasmenya sambil merintih-memohon agar Tiyar melakukannya lagi dan lagi. Ia minta dikulum. Ia minta digigit-gigit kecil. Ia minta ditelusupi-ditelusuri. Ia minta ini, ia minta itu. Semua diberikan oleh Tiyar.
Lalu, lama setelah itu, Rien minta digendong ke kasur yang tergeletak dingin di lantai. Di situ ia minta Tiyar melumat-luluh-lantakkan tubuhnya yang telah telanjang sepenuhnya. Di situ mereka bergumul kekiri-kekanan, depan-belakang, atas-bawah. Lalu Rien minta di atas. Tiyar pun sukarela menggeletakkan tubuhnya yang memang sudah cukup letih. Lalu Rien mendominasi permainan yang seperti tak pernah bisa dihentikan ini. Berkali-kali wanita itu menjerit-jerit kecil, menggigit bibirnya sendiri, meremas bahu Tiyar di bawahnya, menjepitkan kedua pahanya yang sudah basah kuyup oleh peluh mereka berdua. Berkali-kali!
Barulah 95 menit kemudian, … mungkin lebih…., mungkin dua jam kemudian…. keduanya terhempas di pantai pencapaian bersama. Tergeletaklah keduanya dengan nafas terengah-engah dan wajah letih tetapi penuh kepuasan. Kasur dan seprainya sudah awut-awutan centang-perentang basah dan lengket pula di sana-sini. Rien menelungkup di dada lover boy-nya. Ia pejamkan mata dengan nikmat. Dan saat itulah ia berpikir tentang sebuah gerakan kaki untuk proyek tarian berikutnya, yang diberi judul Untuk Langit Untuk Laut (For the Sky, For the Sea). Ia berpikir tentang sebuah gerakan menendang sambil meregang, seperti ketika tadi ia menikmati orgasmenya, entah yang keberapa!
*****
Nama Riendu terus mencuat di dunia panggung. Setelah tariannya, orang mulai melirik kemampuan aktingnya. Sebuah sinetron segera dibuat untuknya dan Rien mendapat banyak sekali uang untuk 12 episode. Baginya, sinetron ini juga tidak terlalu baru karena kisahnya adalah tentang seorang penari ronggeng di sebuah dukuh terpencil. Rien sangat menyukai peran ini karena ia juga bisa “memaksa” sutradaranya memakai beberapa gerakan ciptaannya sendiri.
Hidup Rien mulai gemerlap dan sibuk. Tiyar dengan setia berada di sampingnya, dan Rien bersyukur memiliki pacar yang bisa disandarinya kalau sedang capai, bisa diajak bercanda kalau sedang gundah, dan bisa diajak bercinta kapan saja!
Sinetronnya belum lagi ditayangkan, ketika pada suatu malam di sela shooting seorang asistennya datang membawa sebuah foto seorang anak dara yang minta ditandatangani. Sambil menghirup minuman dingin, dengan acuh tak acuh Rien menerima foto itu dan bersiap-siap membubuhkan tandatangan. Ia sudah siap untuk ini: menjadi populer dan dikejar-kejar pemburu tandatangan. Ia telah buat sebuah tandatangan sederhana yang bisa digoreskan dalam satu gerakan. Ia hampir tak pernah mengamati benda yang ditandatangani. Kali ini pun ia siap menggores, tetapi… sebentar dulu!
“Eh?!” Rien menjerit, tidak jadi menggoreskan tandatangannya, matanya terpaku pada foto gadis di tangannya. Ia kenal gadis itu. Nun di sebuah kota kecil, ia pernah lihat gadis ini. Ia tak pernah lupa matanya yang lembut dan wajahnya yang manis-polos itu.
“Kenapa?” Tiyar menjulurkan kepala dari sebelahnya, ikut memandangi foto itu.
“Aku rasanya kenal anak ini,” kata Rien sambil mengernyitkan dahi.
“Itu foto anak SMA, ada sejuta yang seperti dia,” kata Tiyar seenaknya.
“Justru itu. Aku kenal sewaktu anak ini masih SMA. Sekarang pasti bukan SMA lagi,” kata Rien sambil terus mengamati foto di tangannya.
“Orangnya ada di luar, Mbak,” kata sang asisten yang berdiri patut di sebelah Rien, memberanikan diri menyela.
“Kamu tahu namanya?” tanya Rien.
“Alma,” kata asistennya.
Tentu saja! sergah Rien dalam hati sambil bangkit menarik tangan asistennya dan berkata, “Antar saya ke anak itu!”
Di luar, Alma berdiri gelisah. Ia tidak yakin tindakannya itu bijaksana. Ia memang bermaksud meminta tandatangan sambil mencoba mengadu untung, siapa tahu Mbak Rien masih ingat. Ketika Alma melihat Mbak Rien keluar dari sebuah tenda tempat para artis beristirahat, gadis itu hampir tak mengenalinya lagi. Maklumlah, wanita penari yang cantik itu kini semakin jelita dengan pakaian yang “wah” dan dengan aura yang penuh kharisma. Baru setelah dekat, Alma sadar ia berhadapan dengan Dang Hyang itu, dan lututnya lemas. Lidahnya kelu.
“Hai!” seru Rien riang melihat Alma berdiri terpaku. Ia tidak bisa lupa gadis ini, walau sekarang tampak agak kurus.
“Mbak Rien?” ucap Alma ragu-ragu.
“Ya! Apa kabar kamu, Alma!” seru Rien dengan riang. Tiyar yang melongok dari tenda sempat terheran, tetapi lalu masuk lagi.
Mereka berpelukan, walau Alma sempat kikuk menyambut rentangan tangan seorang bintang. Sedangkan Rien sendiri tanpa canggung menempelkan pipinya ke pipi gadis itu. Kurus sekali dia, pikir Rien sambil membayangkan seorang anak SMA dengan seragam putih abu-abu.
“Mbak tidak lupa kepada saya…,” bisik Alma seperti mau menangis. Sesungguhnya ia terharu diterima seperti ini oleh seseorang yang fotonya menghiasi sampul majalah wanita di seluruh Indonesia.
Rien tertawa sambil mencengkram erat bahu Alma, “Tidak! Mana mungkin Mbak lupa sama cah ayu seperti ini.”
Pipi Alma merona merah, dan sambil tersipu berkata, “Ah, bisa aja, Mbak!”
Hmm…, logatnya sudah seperti anak metropolitan, pikir Rien. Ia lalu menarik Alma untuk ikut masuk ke tenda para artis. Dengan canggung gadis itu mengikutinya. Ia seperti sedang bermimpi, melihat dari dekat para artis yang sedang shooting!
Lalu mereka bercakap-cakap panjang lebar. Terutama Rien yang memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, dan Alma menjawab polos betapa ia kini sudah berpraktek dengan mayat-mayat di rumah sakit, sudah pandai membersihkan nanah dari borok-borok di kaki pasien miskin dan para gembel, sudah pernah melihat darah tumpah ruah dari seorang ibu yang mengalami perdarahan…
“Astaga!… Anak sehalus ini akan menjadi tukang bedah perut orang?” seru Rien sambil tertawa riang. Tiyar ikut tertawa, dan berkomentar, “Asal jangan meninggalkan guntingnya di dalam!”
Alma ikut tertawa, agak lega karena ternyata para bintang itu manusia juga. Bisa bercanda dan tertawa seenaknya. Pastilah mereka makan nasi, dan sekali-kali pasti juga makan tempe, pikir Alma sambil melanjutkan tawanya dalam hati.
Lalu mereka bernostalgia tentang kota kecil nun di sana. Tentang pasar yang satu-satunya, dan tentang stasiun bis kota yang hanya ramai di akhir pekan. Kemudian juga tentang anak-anak peserta sanggar yang kata Alma sekarang sudah berpencaran. Ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi pramugari, ada yang kawin dengan juragan perahu. Tak satu pun yang jadi penari! … Rien tertawa gelak mendengar yang terakhir ini.
“Bagaimana kabar Kino?” tiba-tiba saja keluar pertanyaan itu dari mulut Rien yang sedang tertawa. Dan begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, begitu pula Rien tersadar. Tawanya berhenti. Eh, mengapa aku bertanya tentang dia? sergah hati kecilnya.
Alma ikut terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak siap menjawabnya, karena ia pun tidak tahu kabar pemuda yang sempat mengisi relung-relung terdalam hatinya. Sekarang ia sulit sekali masuk ke relung-relung itu; sulit menemukan apakah nama pemuda bermata lembut yang selalu gundah itu tetap tergores di dinding hatinya.
“Maaf,” kata Rien melihat gadis di depannya terpana tak bisa menjawab. Ah, tetapi apa perlunya minta maaf? sergah hati kecilnya lagi.
“Saya juga tidak tahu, Mbak. Maaf juga,” ucap Alma memelas, tetapi justru tampak lucu. Rien pun segera tergelak untuk mencairkan suasana. Sudahlah, kata hati kecilnya, hentikan pertanyaan tentang pemuda itu.
“Ya, sudah! Kita ngomong yang lain saja,” kata Rien ringan di antara tawanya.
Lalu celoteh mereka berdua berlanjut. Tiyar pun merasa tersingkirkan, dan sambil bersungut pemuda itu meraih sebuah minuman dingin dan berlalu ke arah beberapa kru film yang sedang duduk-duduk main kartu remi.
Kalau saja shooting tidak segera dimulai, mungkin mereka akan bicara sampai berjam-jam lagi. Namun sutradara akhirnya berteriak, orang-orang segera berkemas, Rien pun siap dibedaki dan di-brief untuk adegan berikutnya. Alma tahu diri. Dia segera pamit sambil memohon untuk boleh menemui Rien lagi di lain waktu. Rien tersenyum manis sambil mengangguk, lalu memberikan nomor telepon pribadinya. Alma segera mencatatnya, lalu segera meninggalkan wilayah shooting. Tak sedikit pun ia ingat bahwa fotonya belum lagi ditandatangani!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
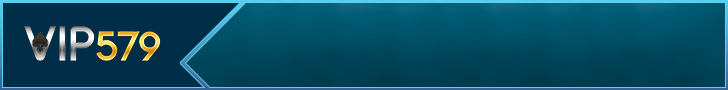
.gif)














